Qiyas
PENDAHULUAN
Definisi Qiyas
Secara
etimologis, kata “qiyas” artinya mengukur, membanding seuatu dengan semisalnya.
Tentang arti qiyas menurut terminology (istilah hukum), terdapat beberapa
definisi berbeda yang saling berdekatan artinya. Diantara definisi-definisi itu
adalah :
- Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa,
memberi definisi qiyas :
“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada
sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan
hokum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan
hukum atau peniadaan hukum.”
- Qadhi Abu Bakar memberikan
definisi qiyas :
“Menanggungkan sesuatu
yang diketahui kepada sesuatu tang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada
keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama
diantara keduanya.”
- Abu Zahrah memberikan definisi
qiyas :
“Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak
ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena
keduanya berserikat dalam ‘illat hukum.”
Qiyas
merupakan suatu cara penggunaan ra’yu untuk menggali hukum syara’ dalam hal-hal
yang nash Al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.
Dasar
pemikiran qiyas itu yaitu adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab.
Hampir dalam setiap hokum diluar bidang ibadah, dapat diketahui alasan rasional
ditetapkannya hukum itu oleh Allah Swt. Alasan hokum yang rasional itu oleh
ulama disebut ‘illat. Disamping itu
dikenal pula konsep mumatsalah, yaitu
kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah. Bila dua hal itu
sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi akibat dari sifat
tersebut. Meskipun Allah Swt hanya menetapkan hukum terhadap satu dari dua hal
yang bersamaan itu, tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi,
meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan hukumnya.
Hal-hal
atau kasus yang ditetapkan Allah hukumnya sering mempunyai kesamaan dengan
kasus lain itu tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah, namun karena ada kesamaan
dalam hal sifatnya dengan kasus yang ditetapkan hukumnya, maka hokum yang sudah
ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus lain tersebut.
Atas
dasar keyakinan bahwa tidak ada yang luput dari hokum Allah, maka setiap Muslim
meyakini bahwa setiap kasus atau peristiwa yang terjadi pasti ada hukumnya.
Sebagian hukumnya itu dapat dilihat secara jelas dalam hal syara’, namun sebagian
yang lain tidak jelas. Diantara yang tidak jelas hukumnya itu mempunyai
kesamaan sifat dengan kasus yang sudah dujelaskan hukumnya. Dengan konsep
mumatsalah, peristiwa yang tidak jelas hukumnya itu dapat disamakan hukumnya
dengan yang ada hukumnya dalam nash. Meskipun secara jelas tidak menggunakan
nash, namun karena disamakan hukumnya dengan yang ada nashnya, maka cara
penetapan hokum seperti ini dapat dikatakan menggunakan nash syara’ secara
tidak langsung. Usaha mengistinbath dan penetapan hokum yang menggunakan metode
penyamaan ini disebut ulama Ushul dengan qiyas (analogi).
Qiyas sebagai Dalil Hukum Syara’
Memang tidak ada
dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan dalil
syara’ untuk menetapkan hokum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan
mujtahid menetapkan hokum syara’ di luar apa yang ditetapkan oleh nash. Oleh
karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan qiyas sebagai dalil
hukum syara’.
Dalam
hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara’, Muhammad Abu
Zahrah membagi menjadi 3 kelompok, yaitu :
- Kelompok Jumhur Ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil syara’. Mereka menggunakan dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nash Al-Qur’an atau Sunnah dan dalam ijma’ ulama. Mereka menggunakan qiyas secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.
- Kelompok ulama Zhahiriyah dan Syi’ah Imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Zhahiriyah juga menolak penemuan ‘illat atas suatu hokum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hokum syara’.
- Kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan illat diantara keduanya; kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas, sehingga qiyas itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Qur’an dan Sunnah.
Argumentasi
ketiga kelompok ulama tentang penggunaan qiyas tersebut, dapat dikelompokkan
lagi kedalam dua kelompok, yaitu: yang menerima dan yang menolak penggunaan
qiyas.
Masing-masing
kelomppok mengemukakan dalil Al-Qur’an, Sunnah, ijma’ ulama atau sahabat dan
dalil ‘aqli.
Dalil yang
dikemukakan Jumhur Ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil syara’ adalah :
1. Dalil Al-Quran
Allah SWT
memberi petunjuk bagi penggunaan qiyas dengan cara menyamakan dua hal
sebagaimana terdapat dalam surat
Yasin ayat 78-79,
“Ia berkata, ‘Siapakah yang akan
menghidupkan tulang belulang sesudah ia berserakan ?’ katakanlah, ‘Yang akan
menghidukannya adalah yang mengadakannya pertama kali.’”
Ayat
ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya menghidupkan tulang
belulang yang telah berserakan dikemudian hari dengan kemampuan-Nya dalam
menciptakan tulang belulang pertama kali. Hal ini berarti Allah menyamakan
menghidupkan tulang tersebut kepada penciptaan pertama kali.
Kelompok
Zhahiriyah menolak argumentasi ini. Mereka mengatakan bahwa Allah SWT tidak
pernah menyatakan bahwa Ia mengembalikan tulang belulang oleh karena Ia yang
menciptakannya pertama kali. Allah juga tidak mengabarkan bahwa penciptaan-Nya pertama
kali mewajibkan untuk mengembalikannya ke bentuk yang pertama lagi. Seandainya
penciptaan tulang pertama kali oleh Allah mewajibkan untuk menghidupkannya
kembali, maka wajib pula Allah melenyapkannya sesudah diciptakannya pertama
kali, dan berarti Allah akan melenyapkan lagi tulang itu untuk kedua kali
sesudah diciptakan yang kedua kalinya. Mengenai hal ini tidak ada seorangpun
yang berpandangan demikian. Kalaupun mungkin begitu, tentu Allah akan
mengembalikan tulang belulang itu ke dunia untuk kedua kalinya sebagaimana
Allah menciptakan manusia pertama kali. Pendapat seperti ini adalah kafir dan
tidak ada yang berpendapat demikian kecuali dalam ajaran reinkarnasi. Karena itu, menurut Zhahiriyah, maksud ayat tersebut
hanyalah sebagaimana arti zhahirnya, yaitu : Yang sanggup menciptakan sesuatu
pertama kali, sanggup pula menghidupkan orang mati.
2. Dalil Sunnah
Diantara dalil
sunnah yang dikemukakan Jumhur Ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan qiyas
adalah :
Hadits
mengenai percakapan Nabi dengan Muaz bin Jabal, saat ia diutus ke Yaman menjadi
penguasa disana. Nabi bertanya, “Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya
kepadamu diajukan sebuah perkara?” Muaz menjawab, “Saya menetapkan hukum
berdasarkan kitab Allah.” Nabi bertanya lagi,”Bila engkau tidak menemukan
hukumnya di kitab Allah?’ Jawab Muaz, ”Dengan sunnah Rasul.” Nabi bertanya
lagi, “ Kalau dalam sunnah engkau tidak menemukannya?” Muaz menjawab, “saya
akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra’yu) saya.” Nabi bersabda, “Segala
puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasul Allah dengan apa
yang di ridhoi Rasul Allah .”
Hadits
tersebut merupakan dalil sunnah yang kuat, menurut Jumhur Ulama, tentang
kekuatan qiyas sebagai dalil syara’.
Namun
hadits itu ditolak oleh zhahiriah, baik dari segi matan (teks) maupun dari segi
sanad (periwayatan).
Menurut
Zhahiri, dari segi sanad hadits itu dianggap gugur, karena tidak seorangpun
meriwayatkan hadits ini diluar jalur periwayatan ini. Indikasi gugurnya itu
adalah: pertama, hadits itu diriwayatkan dari suatu kaum yang namanya tidak
diketahui, karenanya tidak menjadi hujjah atas orang-orang yang tidak
mengetahui siapa perawinya. Kedua, dalam urutan perawinya terdapat Harits ibn
‘Amru yang tidak pernah mengemukakan hadits selain dari jalur ini.
Kelompok
ulama zhahiri juga menilai bahwa hadits tersebut maudhu’ (dibuat-buat) dan
jelas kebohongannya, karena mustahil ada hokum yang tidak dijelaskan dalam
Al-Qur’an padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-An’am (6) ayat 38 :
“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun
didalam Al-Kitab (Al-Qur’an).”
Dari
segi artinya, menurut zhahiri, hadits Muadz itu tidak sedikitpun menyebut
tentang qiyas dengan cara apapun. Dalam hadits itu hanya disebutkan ra’yu ; penggunaan ra’yu tidaklah berarti qiyas. Ra’yu
hanyalah menetapkan hokum dengan cara terbaik, lebih hati-hati dan lebih
selamat akibatnya. Sedangkan qiyas menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada
nashnya seperti hokum sesuatu yang ada nashnya, apakah itu terbaik, secara
hati-hati dan berakibat baik tidak.
3. Atsar Shahabi
Adapun argumentasi
Jumhur Ulama berdasarkan atsar sahabat dalam penggunaan qiyas adalah, Surat Umar
bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy’ari sewaktu diutus menjadi qodhi di Yaman. Umar berkata,
“Putuskanlah hukum berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak
menemukannya, maka putuskan berdasarkan Sunnah Rasul. Jika tidak juga kamu
peroleh di dalam Sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan ra’yu.”
Pesan
Umar dilanjutkan dengan
“Ketahuilah kesamaan dan keserupaan; qiyaskanlah segala urusan waktu
itu”
Bagian
pertama atsar ini menjelaskan suruhan menggunakan ra’yu pada waktu tidak
menemukan jawaban dalam Al-Qur’an maupun
Sunnah; sedangkan bagian akhir atsar shahabi itu secara jelas menyuruh mencari
titik perbandingan dan kesamaan diantara dua hal dan menggunakan qiyas bila
menemukan kesamaan.
Atsar
shahabi tentang pesan Umar kepada Abu Musa Al-Asy’ari itu dibantah oleh ulama
Zhahiriah, baik dari segi sanad maupun dari segi maksud matannya..
Zhahiriyah
menganggap atsar tersebut tidak sah sanadnya karena diriwayatkan dari dua jalur
sanad, pertama melalui Abdul Malik Ibn Wahid Ibn Mi’dan dari ayahnya. Sanad ini
tidak sah karena Abdul Malik sendiri adalah seorang Kufah, periwayatnya matruk (tertolak) dan gugur tanpa
sanggahan dari Ulama. Sedangkan ayahnya sendiritidak dikenal menurut versi Abu
Muhammad; namun dijelaskan oleh Ibn Hazam bahwa perawi ini hanya dilemahkan
oleh Abu Muhammad.
Atsar
tersebut menurut jalur periwayatan kedua adalah munqathi’, karena mulai dari Al-Karji hingga Sofyan, para perawinya
tidak dikenal. Karena itu menjadi batal jika menggunakan atsar tersebut sebagai
dalil.
Syarat dan Rukun Qiyas
Membicarakan
syarat qiyas berarti membicarakan syarat-syarat yang berlaku pada setiap rukun
atau unsure-unsur qiyas. Rukun atau unsure qiyas itu sebagaimana telah
disebutkan adalah :
a.
Maqis ‘alaih (tempat
meng-qiyas-kan sesuatu kepadanya)
Dalam memberikan nama kepada maqis alaih itu terdapat beberapa
pendapat. Ada
yang menamakannya ashal (sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain).
Ada yang
menggunakan istilah wadah/ tempat yang pada wadah itu terdapat hokum yang akan
disamakan kepada wadah lain. Ada
juga yang menyebutnya dengan sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya
hokum. Pendapat lain mengatakan bahwa maqis alaih itu adalah hokum bagi suatu wadah.
Sangat sedikit sekali pengarang yang
mengungkapkan syarat-syarat yang terpenuhi pada ashal maqis alaih, bahkan
kadang-kadangbercampur baur dengan persyaratan hokum ashal. Alasanya barangkali
karena jumhur ulama sendiri tidak mengisyaratkan apa-apa untuk ashal itu.
Meskipun demikian ada juga ulama yang mengemukakan persyaratan sebagai berikut
:
a). Harus ada
dalil atau petunjuk yang membolehkan meng-qiyas-kan sesuatu kepadanya baik
secara nau’i atau syakhsi (lingkungan yang sempit atau maksud terbatas).
Persyaratan ini dikemukakan ‘Utsman
Al-Baththi (‘Utsman ibn Muslim), seseorang ahli fiqh di Bashrah pada masa Abu
Hanifah. Namanya dinisbatkan kepada Al-Baththi karena profesinya sebagai
saudagar pakaian.
Jumhur Ulama menolak persyaratan ini karena
menurut mereka tidak ada dalil yang mensyaratkannya.
b). Harus ada
kesepakatan ulama tentang adanya ‘illat pada ashal maqis ‘alaih itu.
Persyaratan ini dikemukakan Basyir Al-Marisi (Basyir ibn Ghiyas bin Abi
Karimah), salah seorang tokoh kelompok Mubtadi’ah.
Jumhur ulama menolak persyaratan ini,
karena menurutnya tidak ada dalil atau petunjuk yang mempersyaratkannya.
b.
Maqis (sesuatu yang akan disamakan
hukumnya dengan ashal)
Untuk maqis ini kebanyakan ulama menggunakan kata “furu’” (sesuatu yang
dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu yang lain). Ada yang mengatakan bahwa maqis adalah wadah
yang hukumnya diserupakan dengan yang lain. Ada pula yang menyebutnya hukum dari wadah
yang disamakan. Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa furu’ itu adalah
“dalil hukum yang disamakan”, karena yang menjadi dalil tentang adanya hukum
pada furu’ adalah qiyas itu sendiri.
Untuk maqis ini terdapat beberapa syarat. Sebagian dari syarat itu
disepakati para ulama dan sebagian lagi hanya dikemukakan oleh ulama tertentu.
Syarat-syarat maqis itu adalah sebagai berikut :
a.
‘Illat yang terdapat pada furu’
memiliki kesamaan dengan ‘illat yang terdapat pada ashal. Maksudnya seluruh
‘illat yang terdapat pada ashal juga terdapat pada furu’. Jumlah ‘illat pada
furu’ itu bisa sebanyak yang terdapat pada ashal atau melebihi yang terdapat
pada ashal.
b.
Harus ada kesamaan antara furu’
itu dengan ashal dalam hal ‘illat, maupun hukum; baik yang menyangkut ‘ain
‘illat atau jenis ‘illat dan sama dalam ‘ain hukum atau jenis hukum. Bila
diantara hal itu terdapat perbedaan, maka rusaklah qiyas; karena tidak terdapat
‘illat dalam furu’ (dalam hal berbedanya ‘illat) atau tidak adanya hokum ashal
pada furu’ (dalam hal berbedanya hukum.
c.
Ketetapan hukum pada furu’ itu
tidak menyalahi dalil qath’i. Maksudnya, tidak terdapat dalil yang isinya
berlawanan dengan furu’. Hal ini dapat disepakati oleh ulama. Alasannya adalah
bahwa qiyas tidak dapat digunakan pada sesuatu selama masih ada dalil qath’i
yang berlawaann dengannya.
d.
Tidak terdapat “penentang” (hukum
lain) yang lebih kuat terhadap hokum pada furu’ dan hokum dalam penentang itu
berlawanan dengan ‘illat qiyas itu. Penentangnya itu bisa dalam bentuk naqid
(contradictory) atau dalam bentuk dhid (contrary).
e.
Furu’ itu tidak pernah diatur
hukumnya dalam nash tertentu; baik materi nash itu bersesuaian dengan hukum
yang akan ditetapkan pada furu’, atau berlawanan dengannya.
f.
Furu’ (sebagai maqis) itu tidak
mendahului ashal (sebagai maqis ‘alaih) dalam keberadaanya. Umpamanya
mengqiyaskan “wudhu” kepada “tayammum” dalam menetapkan kewajiban “niat”. Wudhu
itu itu lebih dahulu adanya daripada tayammum. Wudhu disyariatkan sebelum
hijrah, sedangkan tayammum disyariatkan sesudah hijrah. Lagipula ditetapkannya
tayammum itu adalah sebagai pengganti wudhu di saat tidak dapat melakukan
wudhu.
Perbedaan Hukum Ashal dan Furu’
a.
Makna ashal dan furu’
.Islam adalah Aqidah, Syariat
dan Akhlaq. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya
saling terkait dan saling menyempurnakan. Ketiganya terhimpun dalam Ajaran
Islam melalui dua ruang ilmu, yaitu : Ushuluddin dan Furu’uddin
. Ushuluddin
biasa disingkat ushul/ashal, yaitu ajaran Islam yang sangat prinsip dan
mendasar, sehingga umat Islam wajib sepakat dalam ashal dan tidak boleh
berbeda, karena perbedaan dalam ashal adalah penyimpangan yang mengantarkan
kepada kesesatan.
Sedang Furu’uddin
biasa disingkat furu’, yaitu Ajaran Islam yang sangat penting namun tidak
prinsip dan tidak mendasar , sehingga umat Islam boleh berbeda dalam furu’,
karena perbedaan dalam furu’ bukan penyimpangan dan tidak mengantarkan kepada
kesesatan, tapi dengan satu syarat yakni : ada dalil yang bisa
dipertanggung-jawabkan secara Syar’i.
Penyimpangan
dalam Ushul tidak boleh ditoleran, tapi wajib diluruskan. Sedang Perbedaan
dalam Furu’ wajib ditoleran dengan jiwa besar dan dada lapang serta sikap
saling menghargai.
b. Menentukan Ashal dan Furu’
Cara
menentukan suatu masalah masuk dalam ashal atau furu’ adalah dengan melihat
kekuatan dalil dari segi wurud (Sanad Penyampaian) dan dilalah
(fokus penafsiran).
Wurud
terbagi dua yaitu :
1. Qoth’i yaitu dalil yang sanad
penyampaiannya mutawatir,
2.
Zhonni yaitu dalil yang sanad penyampaiannya tidak mutawatir.
Mutawatir
ialah sanad penyampaian yang perawinya berjumlah banyak di tiap tingkatan,
sehingga mustahil mereka berdusta.
Dilalah juga
terbagi dua yaitu :
1. Qoth’I yaitu dalil yang hanya
mengandung satu penafsiran
2.
Zhonni yaitu dalil yang mengandung multi penafsiran
Karenanya,
Al-Qur’an dari segi wurud semua ayatnya qoth’i, karena sampai kepada kita
dengan jalan mutawatir. Sedang dari segi dilalah maka ada ayat yang qoth’i
karena hanya satu penafsiran, dan ada pula ayat yang zhonni karena multi
penafsiran.
Sementara
As-Sunnah, dari segi wurud, yang mutawatir semuanya qoth’i, sedang yang tidak
mutawatir semuanya zhonni. Ada
pun dari segi dilalah, maka ada yang qoth’i karena satu pemahaman dan ada pula
yang zhonni karena multi pemahaman.
Selanjutnya,
untuk menentukan klasifikasi suatu persoalan, apa masuk ashal atau furu’, maka
ketentuannya adalah :
-
Suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud dan
dilalah sama-sama qoth’i, maka ia pasti masalah ashal.
-
Suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud dan
dilalah sama-sama zhonni, maka ia pasti masalah furu’.
-
Suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud qoth’i
tapi dilalahnya zhonni, maka ia pasti masalah furu’.
-
Suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud zhonni
tapi dilalahnya qoth’i, maka ulama berbeda pendapat, sebagian mengkatagorikannya
sebagai ashal, sebagian lainnya mengkatagorikannya sebagai furu’.
Dengan demikian,
hanya pada klasifikasi pertama yang tidak boleh berbeda, sedang klasifikasi
kedua, ketiga dan keempat, maka perbedaan tidak terhindarkan.
c. Contoh ashal dan furu’
1. Dalam Aqidah
Kebenaran
peristiwa Isra Mi’raj Rasulullah SAW adalah masalah ashal, karena dalilnya
qoth’i, baik dari segi wurud mau pun dilalah. Namun masalah apakah Rasulullah
SAW mengalami Isra’ Mi’raj dengan ruh dan jasad atau dengan ruh saja, maka
masuk masalah furu’, karena dalilnya zhonni, baik dari segi wurud mau pun
dilalah.
Karenanya,
barangsiapa menolak kebenaran peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW maka ia
telah sesat, karena menyimpang dari ashal aqidah. Namun barangsiapa yang
mengatakan Rasulullah SAW mengalami Isra’ Mi’raj dengan ruh dan jasad atau ruh
saja, maka selama memiliki dalil syar’i ia tidak sesat, karena masalah furu’
aqidah.
2. Dalam Syariat
Kewajiban shalat
lima waktu
adalah masalah ashal, karena dalilnya qoth’i, baik dari segi wurud mau pun
dilalah. Namun masalah apakah boleh dijama’ tanpa udzur, maka masuk masalah
furu’, karena dalilnya zhonni, baik dari segi wurud mau pun dilalah.
Kewajiban shalat
lima waktu
adalah masalah ashal, karena dalilnya qoth’i, baik dari segi wurud mau pun
dilalah. Namun masalah apakah boleh dijama’ tanpa udzur, maka masuk masalah
furu’, karena dalilnya zhonni, baik dari segi wurud mau pun dilalah.
3. Dalam Akhlaq
Berjabat
tangan sesama muslim adalah sikap terpuji adalah masalah ashal, karena dalilnya
qorh’i, baik dari segi wurud mau pun dilalah. Namun masalah bolehkah jabat
tangan setelah shalat berjama’ah, maka masuk masalah furu’, karena Dalilnya
zhonni, baik dari segi wurud mau pun dilalah.
Karenanya,
barangsiapa menolak kesunnahan jabat tangan antar sesama muslim, maka ia telah
sesat, karena menyimpang dari ashal akhlaq. Namun barangsiapa yang berpendapat
tidak boleh berjabat tangan setelah shalat berjama’ah atau sebaliknya, maka
selama memiliki dalil syar’i ia tidak sesat, karena masalah furu’ akhlaq.
.

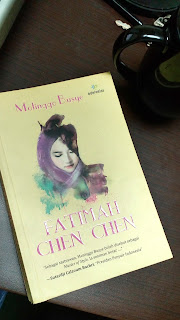
Komentar
Posting Komentar